01 Jan Peta Majas Media @masdalu (Bag. 2)
Meskipun “fakta teoretik”-nya masih dapat berlaku bagi praktik-praktiknya hingga sekarang, sebagaimana yang tertera dalam salah satu teori konvensional tentang humor[1] yang sering diacu (oleh kebanyakan akademisi di ranah psikologi dan sosial), bahwa humor biasanya dapat dicapai tatkala dua syarat terpenuhi (yaitu, adanya [1] “keganjilan” dan [2] “resolusi atas keganjilan tersebut sebagai punchline”), aksi-aksi komedi kontemporer yang umumnya termediasi oleh media sosial perlu dipahami dengan cara yang berbeda.
Saya kira, poin kelucuan pada “Yha Challenge” atau “Seberapa Greget Lo?”, sebagai contoh, dapat terjadi (dan terakumulasi) bukan hanya karena adanya kalimat yang saling beroposisi (atau paradox), ataupun adanya pembelokan ekspektasi penonton, tapi juga karena ada “atribut pemicu” yang menjadi alat utama penegas punchline mereka. Yang mesti digarisbawahi dari dua contoh ini adalah aspek pragmatik[2] dari suatu pernyataan jenaka yang di-perform-kan. Aspek itu dapat diteliti dari, pertama, karakteristik mediumnya, yaitu moving image (atau video) yang diviralkan, dan kedua, dari bagaimana konten lucu dan ekspresi yang menyertainya diujarkan. Konteks moving image yang saya maksud tentunya merujuk kepada fenomena video online karena konten-konten lucu ini memang bertujuan untuk menjadi viral, di media sosial bukan di televisi, dan hadir sebagai image yang vernakular. Sedangkan cara ujaran, itu berkaitan dengan apa saja elemen-elemen naratif dan visual yang digunakan si pembuat di dalam kontennya.
Pada contoh yang pertama, “atribut pemicu” yang saya maksud ialah seruan “Yha!”, sebagai satu bagian dari act of speech, yang diteriakkan sembari memperagakan gerakan yang menunjukkan rasa “geli”, serentak beramai-ramai oleh para pelawak—atau para awam yang bermaksud mem-perform-kan tindakan melawak—di dalam video yang mereka unggah.[3] Pada contoh kedua, biasanya dilakukan dengan menampilkan teriakan seru, seperti “Wooo!”, yang menyiratkan pujian: “Betapa jeniusnya jawabanmu!” atau “Lo swag banget, Bro!”, lengkap dengan efek visual yang menegaskan ulang nuansa ke-swag-an yang dimaksud sebagai poin kelucuan. Selain itu, sering kali di dalam seri kalimat jenaka yang di-perform-kan pada video “Seberapa Greget Lo?”, si pembuat menyelipkan satu atau dua ujaran ironis dengan menyinggung topik “jomblo”—dan pada bagian ini, yang bekerja adalah teori superioritas dalam humor. Tapi yang menarik untuk dipikirkan ulang, efek-efek visual yang mereka gunakan (jika ada) mungkin bukan dalam niatan/kerangka pikir seorang pembuat film yang berusaha menyentuh emosi penonton, tetapi sebagai mocking (dan lebih spesifik: mocking atas karakteristik teknologi medianya sendiri), dan karenanya sangat efektif sebagai “komedi-receh visual” ala netizen.
Menurut saya, dua kasus di atas bisa kita maknai juga sebagai contoh dari “tiga aspek yang tak terucapkan dalam humor” yang diajukan oleh Marlene Dolitsky,[4] atau contoh lain dari pemanfaatan metode yang belajar dari fenomena “wabah tawa Tanganyika”: jika tawa bisa menular (dan ditularkan) maka penularan tawa pun bisa dipicu. Metode ini, saya pikir, juga digunakan oleh banyak YouTuber ketika menyunting video-video mereka, baik dari cara mereka mengonstruksi gambar maupun dari cara mereka menghadirkan “subjek penggembira” untuk memancing penonton agar ikut tertawa. Memang, ini bukan metode yang baru karena televisi sudah menerapkannya lebih dulu. Bukankah tepat juga jika kita mengatakan bahwa konten-konten awam di YouTube sudah banyak yang terjebak pada gaya hiburan khas televisi yang lebih dulu populer sejak generasi-generasi sebelum millennial? Tapi, paling minimal, dari sini kita bisa melihat lebih jelas apa yang membuat konten-konten video itu tetap “lucu”.
Saya sengaja menyoroti “atribut pemicu” di dalam dua kasus “video lucu” yang viral sejak setengah tahun lalu itu karena, setelah memikirkannya cukup lama (hampir setahun), saya berpendapat bahwa konten-konten “video lucu” semacam itu relatif tidak lucu jika dinilai dari segi substansialnya. Apalagi kalau kita menganalisanya dengan menggunakan “teori-teori besar” dalam disiplin komedi dan humor. Mungkin ini pula alasan yang menyebabkan munculnya istilah “humor receh”. Akan tetapi, ternyata konten-konten receh tersebut, yang dipandang sebelah mata oleh para snob, juga memiliki suatu daya yang tetap bisa melepas “energi psikis” (yang terwujud dalam bentuk tawa) yang dimaksud Freud. Walau tak lucu, kita tetap tertawa, atau setidaknya tersenyum. Paling tidak, itu yang saya alami: saya sering tertawa menyaksikan video-video “Yha Challenge” ataupun “Seberapa Greget Lo?” di waktu-waktu dini hari ketika mata saya tak kunjung terpejam akibat mengonsumsi media sosial.
***
Konon Louise Michel pernah berkata bahwa puisi telah menjadi milik semua orang sebagaimana halnya drama yang tak lagi melulu ditemukan di dalam teater.[5] Peter Snowdon pun berargumen bahwa moving image juga mengalami hal yang sama. Kini kita pun bisa berargumen—dengan menyadari buntut dari fenomena semakin membuminya segala hal yang berkaitan dengan aktivitas bermedia ini ke masyarakat—bahwa komedi juga telah menjadi milik semua orang.
Maksud saya tentang “kepemilikan” ini bukan berarti bahwa dahulunya komedi tak dimiliki semua orang. Saya pribadi percaya bahwa komedi atau humor sesungguhnya lahir dari keseharian masyarakat. Sementara, “kepemilikan” yang saya maksud itu sehubungan dengan bagaimana “kelucuan” itu dikemas dan didistribusikan lewat alat-alat produksi (media) yang kini sudah mudah diakses. Untuk memproduksi dan menyajikan konten humor, orang-orang tak membutuhkan kemampuan khusus layaknya seorang komedian profesional. Bagi yang ingin melucu di media sosial, mereka cukup ikuti perkembangan tagar terbaru, lalu konstruk kontennya sesuai rules (dengan mengadopsi atau mengulangi konten-konten serupa yang sudah beredar), lalu tinggal tunggu hasilnya: berapa like dan repost yang akan kita dapat. Dan bisa dispekulasikan, tidak sedikit netizen akan terhibur dan bahkan terpicu untuk menjadi “komedian” pula. Soal apakah fase berikutnya si creator akan menjadi terkenal dan berhasil mendulang kekayaan dari aktivitas tersebut, itu hanyalah dampak ekonomis yang lumrah dalam persaingan media, tapi dengan adanya fakta di atas, rasa-rasanya kita cukup beralasan untuk menyebutnya demikian: mereka telah menjadi “pembuat konten humor”.
Lalu, muncul pertanyaan di kepala saya: apakah gerangan yang akan terjadi jika, dari konten-konten humor yang termediasi oleh media sosial itu, kita penggal dan buang aspek “performativitas teknologi medsos” yang melekat pada mereka? Jika itu mungkin direalisasikan, apakah mereka akan tetap mengandung sense of humour yang nilainya sama dengan keadaan mereka ketika sebelum dipenggal? Jika konten-konten tersebut diadopsi ke dalam drama di ranah teater, apakah penonton akan tertawa karena nilai kelucuan yang murni lahir dari substansi tekstualnya, atau justru hanya karena ada memori kolektif di kepala penonton tentang keberadaan media sosial yang telah menjadi latarbelakang sosial hampir seluruh elemen masyarakat dewasa ini? Apakah mereka sebenarnya semata merupakan in-jokes di lingkungan netizen, atau juga akan bernilai humor di mata orang-orang bukan user? Atau, apakah itu semua hanyalah humor-humor kolot yang sudah/sedang berganti tempat distribusi saja? Apakah media sosial itu sendiri memiliki signifikansi tertentu dalam proses terbentuknya persepsi user atas makna konten-konten tersebut, atau tidak?
Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu baru akan bisa dijawab dengan tepat jika kita melakukan suatu penelitian panjang dan mendalam dengan menerapkan metode, pendekatan, dan begitu banyak variabel yang memusingkan kepala. Namun, untuk sementara saya mencoba percaya bahwa “aspek teknologis dari media sosial” memainkan peran yang penting dalam fenomena merebaknya konten-konten humor ala medsos tersebut, bukan dalam hal produksi dan distribusi saja, tetapi juga aspek estetika humornya. Ini pun bukan sekadar soal dari mana konten humor itu lahir dan kemudian menjadi fenomenal (antara offline dan online). Lebih dari itu, perbedaan ranah media itulah yang sesungguhnya bisa kita jadikan picuan untuk berpikir bahwa karakter dari setiap konten yang kita konsumsi sehari-hari memiliki kekhasan: kodrat dari konten media online (khususnya media sosial) jelas berbeda dengan konten-konten di media konvensional. Misalnya, logika humor pada kalimat semacam “Ya, iyalah, masa ya, iya, dong!” yang—seingat saya—pernah populer di dalam dialog pada tayangan sinetron di televisi atau di dalam pecakapan sehari-hari kaum remaja, tidak akan laku dalam logika video “Yha Challenge” sekarang ini, sebagaimana halnya mekanisme humor dalam “20 Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Waktu Putus”-nya Chandra Liow (2014) akan sulit menemukan punchline-nya jika dipertunjukan dalam acara stand-up comedy ala televisi yang, kebanyakan, tampil abusive. Dan “Kejahatan Dunia Maya! Medan Garis Keras!” (2016) yang menjadi bagian dari seri Medanegle-nya Kamaratas! adalah sebuah lompatan dalam perkembangan “humor performatif”, dan lompatan itulah yang selama ini gagal dilakukan oleh produser-produser program reality show televisi.
***
Praktik artistik Dalu Kusma melalui karyanya, @masdalu, berusaha membingkai fenomena “receh” ini, dan/atau berada di sirkulasi isu-isu tersebut. Kita pun dapat menelaah bahwa negotiation theories dan frame theories (dalam mazhab sosiologis), dan incongruity-resolution theory—sebagaimana yang di-mention oleh Mulder dan Nijholt—serta pendekatan analisa wacana kritis sangat relevan untuk memahami derajat humor yang terkandung di dalam teks-teks @masdalu.
https://www.instagram.com/p/BqZqwotnixv/
Kita juga dapat menyadari bahwa, pada teks-teks @masdalu yang mendokumentasikan isu “drama-drama receh percintaan”, Dalu Kusma secara sadar mengamini “atribut pemicu” yang sudah saya coba jelaskan di atas, tetapi ia memanfaatkannya dengan kasat mata dan telinga; karena basis karyanya adalah teks-image, bukan audiovisual, maka “atribut pemicu” justru akan “di-perform-kan” dengan sendirinya oleh netizen. Yang malahan terjadi ialah, ia menerakan caption yang menyimpang sama sekali dari pesan tipografinya. Ini juga merupakan cara komedi ala @masdalu dalam menciptakan “pelepasan energi psikis” (baca: tawa): ekspektasi netizen atas caption—yang diasumsikan [seharusnya] berkaitan dengan teks tipografi—diruntuhkan oleh Dalu dengan memberikan caption yang tak nyambung sehingga “resolusi atas keganjilan”—yang sebelumnya dihasilkan dari kelucuan dalam tipografi—dikembalikan menjadi “keganjilan” sekunder untuk diresolusikan lagi sebagai suatu kesatuan “tipografi+caption”. Dengan kata lain, lawakan @masdalu adalah “humor berganda”, dan metode “humor berganda” @masdalu, menurut saya, adalah yang paling efektif di antara akun-akun lain yang mencoba metode lawakan serupa.
Paragraf di atas adalah sebuah analisis progresif terhadap @masdalu dalam konteks alamnya di media sosial. Kata kunci “humor”, atau “komedi”, dalam catatan ini, saya gunakan sebagai pisau bedah justru untuk memetakan gaya bahasa @masdalu, bukan untuk membuktikan eksistensi dari aspek ke-humor-annya. (Meskipun sebenarnya, secara teoretik, rujukan yang saya gunakan dapat menegaskan nilai komedi karyanya).
https://www.instagram.com/p/BrcjVVHHTtb/
https://www.instagram.com/p/BnbCL2bh66I/
https://www.instagram.com/p/BiPW__UFRHg/
https://www.instagram.com/p/BhG7GLYFBJr/
https://www.instagram.com/p/Be7SDhMF25-/
https://www.instagram.com/p/BejmvdDlJ1T/
https://www.instagram.com/p/BeKARsyl-QL/
https://www.instagram.com/p/BZ9HENSl7a5/
https://www.instagram.com/p/BYJg9oBlvtR/
https://www.instagram.com/p/BWSrrFKFYFU/
https://www.instagram.com/p/BS5OcDAl3uF/
https://www.instagram.com/p/BRVE-HDl5QM/
https://www.instagram.com/p/BPmRrLzjCVZ/
https://www.instagram.com/p/BPhwkMTDb7x/
https://www.instagram.com/p/BPcAEqjDUkZ/
https://www.instagram.com/p/BMxyKtrDLWq/
Dalam rangka memahami lebih jauh gaya bahasa itulah, pertanyaan yang sama dapat kita ajukan: bagaimana jika metode @masdalu ini ia terapkan di alam offline? Apa yang akan terjadi jika Dalu Kusma melompat dari dunia online dan justru bereksperimen di ruang fisik menggunakan tipografi untuk mengolah rekaman-rekaman recehnya itu?
Proyek residensi Dalu Kusma di Bengkel Tiga dan Empat, bisa dibilang, sedang menapaki kemungkinan tersebut sebagai upaya dari Dalu sendiri untuk menelaah dan membuka pemahaman baru atas praktik artistiknya secara lebih mendalam. Visinya bukan melulu harus humor, tetapi bisa jadi suatu imajinasi sastrawi yang lain, yang tak kalah performatifnya, tentu saja. *
Catatan Kaki
[1] Lihat M.P. Mulder & A. Nijholt, (2002), “Humor research: State of the art”, CTIT Technical Report series, hlm. 02-24. Diperoleh 1 Januari 2019 dari situs web Anton Nijholt.
[2] Saya merujuk istilah “pragmatik” dalam linguistik.
[3] Memang harus beramai-ramai! Cobalah tinjau video “Yha Challenge” yang dilakukan oleh satu orang, kita tidak akan mendapatkan efek humor sebagaimana mestinya, kecuali jika menertawakan kekonyolan tersebut.
[4] Lihat Marlene Dolitsky, (2009), “Aspects of the unsaid in humor”, Humor – International Journal of Humor Research, 5(1-2), hlm. 33-44. Diperoleh 1 Januari 2019, dari doi:10.1515/humr.1992.5.1-2.33
[5] Saya kutip kalimat ini dari penggalan yang dikutip dan diterjemahkan oleh Peter Snowdon dalam jurnalnya yang berjudul “The Revolution Will be Uploaded: Vernacular Video and the Arab Spring”, Culture Unbound, Volume 6, 2014: 401–429.
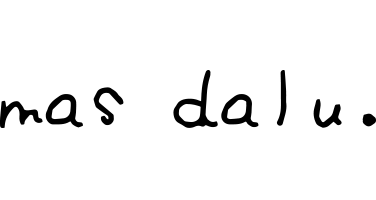
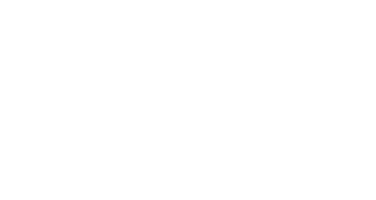
Sorry, the comment form is closed at this time.