15 Nov Peta Majas Media @masdalu (Bag. 1)
Pengalaman pertama saya —kalau meminjam istilah Moetidjo, dinamakan “pengalaman estetis” (yang entah mengapa suatu ketika ia menyebut bahwa pengalaman inilah yang secara alam bawah sadar menuntun awam menikmati dimensi artistik itu)— terhadap “puisi-puisi kontemporer” @masdalu justru terjadi di media sosial Facebook.

Melihat pola yang sama terjadi pada beberapa post-nya kala itu, saya menyadari bahwa akun @masdalu dibuat bukan untuk iseng belaka, melainkan “proyek bermain” yang pembahasannya bisa menjadi sangat serius; proyek dengan tingkat seriusitas yang bisa mencapai titik ludic ekstrem.
Saat itu, saya (dan orang lain juga, tentunya) dengan mudah mengetahui, meskipun melihatnya di Facebook, bahwa @masdalu adalah akun Instagram (karena memang identitas ke-instagram-annya tidak dihilangkan oleh Facebook sama sekali, bahkan ditegaskan —dan begitulah nyatanya bahwa dua layanan ini memang memiliki hubungan dalam konteks bisnis, bahkan dimiliki oleh satu perusahaan yang sama).
Terkait hal itu, yakni fenomena post Instagram yang ditentukan (oleh si pemilik akun) untuk secara otomatis terbagi ke halaman Facebooknya, sebagaimana layanan jejaring sosial lainnya juga menyediakan fasilitas untuk menerapkan hal yang persis, tertunjukkanlah aspek lain dari ke-ludic-an media sosial dalam mewadahi hasrat virtual yang sudah begitu wajar terjadi sejak forum-forum online hadir di masyarakat kita: hasrat kehadiran beriring potensi strategis dari manajemen media [yang bisa dinilai ‘alternatif’ dari sudut pandang tertentu], suatu keniscayaan tentang “narsis yang [justru] diperlukan”. @masdalu tentunya menyadari hal ini, mengingat latar belakang aktivitasnya saat itu yang memang bersinggungan dengan aktivisme pemberdayaan media. Dalu Kusma, pengelola akun tersebut, adalah seniman dan bukan netizen sembarangan. Perlu kita ingat juga, tentunya, bahwa kesadaran semacam itu memang sudah tidak istimewa lagi sekarang ini karena hampir semua orang melakukannya.

Hasrat kehadiran itu, yang beriring potensi strategis dari manajemen media [alternatif], sebuah keniscayaan tentang “narsis yang diperlukan”, yang (tidak bisa ditampik) dibayangi oleh payung-payung kapital (dalam beragam bentuk dan dari berbagai sumber kemungkinan), pada akhirnya, akan menuntut orang-orang kreatif —orang-orang semacam seniman @masdalu ini, salah satunya— untuk bersedia melancarkan suatu negosiasi yang bahkan tidak lagi bisa dikatakan perifer demi mengafirmasi “racun kemudahan” medan sosial milenial, serta merayakannya sebagai trampolin untuk mengkritisi sistem kapital media itu sendiri. Agaknya, ini bisa menjadi sebuah exemplary account tentang seni yang memiliki bahasa berupa aksi —yaitu seni aksi yang faktor-faktor sosialnya sudah sangat termodifikasi pada zaman mutakhir, bukan seni-seni aksi yang telah dikomentari di masa-masa lampau di dalam beberapa mazhab— terutama untuk medan kultural di masyarakat kita sekarang.
Pada konteks ini, saya melihat bahwa teks-teks @masdalu adalah image, dan image-nya adalah teks. Kalimat-kalimatnya bukanlah slogan ataupun jargon, tapi trivia-trivia yang dibingkai dengan pendekatan sastra dan penuh pertimbangan. Upaya branding-nya ialah emansipasi, sedangkan “bisnis online”-nya bersifat kultural. Popularitas akunnya bukan dipicu oleh latar belakang si pemilik akun, sementara selebritasnya didayakan sebagai posisi tawar untuk mengarahkan opini publik.
Sementara itu, sebagaimana saya secara pribadi meyakini, mereka yang abai melakukan jenis negosiasi yang saya sebut di atas itu, perlahan akan tenggelam pada waktunya; mereka akan melebur jadi butir-butir informasi belaka yang membanjiri 24 jam kita, atau terseret dan menjadi bagian dari arus sistem yang tak pernah berhenti diprotes oleh gelombang massa yang selalu muncul setiap tahun (1 May) di hampir semua belahan dunia. Perlu digarisbawahi, negosiasi yang saya maksud tentu saja bukan “negosiasi yang manut”, tapi negosiasi yang tahan banting; negosiasi yang bisa dengan lantang berseru, “Fuck to ‘endorsement’!” Dalu Kusma lewat akun @masadalu-nya, menurut saya, berada di jalur yang mengedepankan kritisisme terhadap fenomena celebrity endorsement ataupun social-media-celebrity-wannabe endorsement di ranah pemasaran media sosial.
Bahasa Media @masdalu dalam Konteks Zaman Layar Genggam

Kita perlu mengakui bahwa @masdalu adalah salah satu manifestasi dari performativitas netizen literer. Praktik sastranya jelas bukan dengan kerangka konvensional, bukan seperti sastrawan yang mendadak menggunakan media sosial. Ia bukan sastrawan bermental kertas, tetapi bermental layar (genggam).
@masdalu adalah suatu tanggapan yang sangat konteks dengan situasi bermedia sekarang, yang memadukan euforia generasinya sendiri dengan kegembiraan a la Mekas, yaitu suatu kegembiraan yang lahir tatkala si tua yang sangat enerjik dan berjulukan Bapak Sinema Avant-garde Amerika itu menyambut internet, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Mekas berikut ini:
...my knowledge of what’s happening in net poetry is very limited. But I think it’s a very open, rich field of activity there, and the net poetry will develop its own, new, forms specific to the medium.(1)
Nyatanya, memang ada banyak akun yang seperti @masdalu ini. Ia pun bukan yang pertama kali menerapkan metode pengelolaan akun media sosial seperti itu. Tapi, saya kira @masdalu melakukan praktiknya dengan sentuhan semiologi Barthes, sadar tidak sadar, melalui cara yang lain sama sekali dari para pengkaji ataupun aktivis media.
Teks-image milik @masdalu bukan hanya tentang bagaimana mengelola media penyampai pesan atau pemicu persoalan, karena faktanya, isi dari terbitan-terbitannya justru membingkai hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Tapi lewat kalimat-kalimat tentang hal remeh-temeh itu, @masdalu tampak sedang berusaha mencari rumusan baru bagi gagasan-gagasan ideal mengenai mental “media sosial” dan “perangkat pintar”, sebagai suatu kontinuitas dari “mental cetak” yang disusul “mental teknologis”, melalui pendekatan yang sangat sederhana, yakni dengan cara yang tak ada bedanya dengan apa yang kita —para netizen— lakukan setiap hari ketika menggunakan gawai. Dengan kerangka berpikir yang kembali ke dasar dan tanpa perlu berrumit-rumit dengan benda-benda teknis dan kode-kode digital, ataupun visual-visual cantik dan canggih (karena ia ternyata malah memilih tipografi yang sederhana saja), dan tidak juga berkutat dengan jargon “oprek-oprek teknologis” itu, @masdalu justru menjadi salah satu seniman yang ikut menggugah medan sosial dari masyarakat penonton, prosumer kontemporer, karena memicu pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana bentuk-bentuk gejala yang muncul dari publik ketika menanggapi postingan-postingannya. Pertama, lewat siratan makna dari konten teks-image-nya; kedua lewat “aksi nge-post” yang dengan sadar menyiasati aturan main prime-time layanan media sosial tempatnya bernaung.
Menyinggung poin kedua pada kalimat terakhir paragraf di atas, kesadaran untuk menyiasati “aturan main prime-time” yang saya maksud, sebenarnya, juga dimiliki oleh para pengelola-pengelola akun media sosial terkenal yang lain, atau oleh mereka yang memiliki orientasi untuk “terus exist di linimasa”. Kita pun bisa dengan mudah mengetahuinya, karena para pemilik layanan media sosial juga memang mengumumkan tata aturan main itu. Akan tetapi, yang menarik dari @masdalu ialah, ia melakukan siasat itu dengan kesadaran dan tujuan kultural. Dan demi visi itu, teks-image @masdalu menjadi berbeda dengan isi dari teks-teks kuotasi inspiratif, galau, kritik-diri, dan lawakan lainnya yang umum kita temui.
@masdalu adalah sebuah permainan tentang mitos-mitos tekstual dan logika-logika semiologis. Inspirasi pembacaan tentang praktik Dalu Kusma dalam @masdalu bisa jadi lahir bukan dari celotehan-celotehannya, tetapi justru dari “ketimpangan alur teks” yang ia sengaja bentuk dan wacanakan. “Ketimpangan alur teks” tersebut —atau lebih tepatnya, “ketidaknyambungan yang disengaja” yang dapat kita lihat antara teks-image pada post dan teks pada caption— adalah tawaran permainan @masdalu yang merupakan sebuah ide estetik daripada sekadar tampilan “sok-sok ngawur agar terkesan artsy“. Ide “ketidaknyambungan yang disengaja” itu —sekali lagi, apakah ini disadari atau tidak oleh si seniman— mengandung nilai referensial dalam konteks praktik kesenian kontemporer di Indonesia. Saya teringat model struktur-tak-sinkron dalam sebuah karya visual-dan-teks berjudul “samsudin.mengapa.engkau.apa..” yang dibuat oleh satu-satunya seniman pixel Indonesia, yaitu oomleo, salah seorang seniman generasi sebelum milenial yang boleh dibilang mempopulerkan gaya bahasa semacam ini di periode 2000-an. Dan pada @masdalu, kesadaran estetik itu dilakukan dengan intensitas yang tinggi dan dalam kuantitas yang patut dilihat, membuahkan kualitas pola yang menggiurkan untuk diinterpretasi sehubungan dengan dinamika netizen yang mengonsumsi (dan mereproduksi) konten @masdalu, dan secara perlahan menjadi suatu disiplin berbahasa pula.

Menambahkan argumentasi lainnya yang bisa kita susun untuk mempertahankan pendapat bahwa “ketimpangan alur teks” @masdalu bukanlah hal yang dingawur-ngawurkan, saya mencoba mengacu salah satu gagasan teoretik dasar mengenai “bahasa gambar bergerak”, yaitu ideogram. Argumentasinya bisa dipaparkan sebagai berikut:
Dalam sebuah kalimat, kutipan-kutipan (citations) bukanlah bagian dari apa yang diharuskan menjadi sebuah montase. Tapi, akan berbeda kasusnya jika kita meletakkan kata (atau kalimat) di dalam bingkai (frame) sebuah layar (dari sebuah gambar bergerak), atau jika kita memfungsikan kata itu sebagai image.
Kata-kata pada layar genggam kita, kata-kata di Instagram Stories kita, misalnya, atau segala macam kuotasi inspiratif yang “menyerang” kita hampir setiap hari layaknya doktrin-doktrin Rumi dan Shakespeare jaman now, menjadi berarti jika kita mau melihatnya sebagai referensi yang didekontekstualisasi dan/atau sebagai image. Karakteristik-karakteristik dari kata-kata itu sebenarnya telah berubah oleh layar gawai, dalam arti bahwa ruang dari kata-kata itu “…telah kehilangan orientasi dan batas-batasnya, dan dihadirkan ke dalam imajinasi tanpa batasan apa pun.” Kata-kata itu “…dengan kata lain, telah menghadapi sifat-sifat spasial dari sinema dan menjadi bagian dari dunia ‘picturable‘ yang berada di luarnya pada segala segi.” (Saya mengutip kalimat kunci dari esai André Bazin, 1967, di sini.)
Layar/bingkai durasional menawarkan kita sebuah cara melihat (way of seeing) yang berbeda, juga sebuah cara membaca (manner of reading) yang berbeda. Layar yang bisa “digeser” memberi kita sebuah cara pengurutan (way of sequencing) yang berbeda pula; kita memiliki cara yang berbeda dalam mengurutkan kata-kata. Ketika kita membaca dengan menyentuh layar dan menyapukan jari-jari kita di atasnya untuk melihat lanjutan kata, kalimat, atau isi keseluruhan sebuah konten, kita sesungguhnya bukan sedang melakukan tindakan seperti “membalik sebuah halaman”, tetapi justru sedang “menggerakkan” kata-kata (atau, dalam konteks esai ini, kata-kata yang telah menjadi image-image itu). Menggeser atau “membalik (to flip)” isi layar (yang sebenarnya sudah teranimasikan oleh logika komputer) tersebut, dalam konteks penggunaan gawai berlayar sentuh atau smartphone, adalah sebuah tindakan yang sesungguhnya “menggerakkan” elemen-elemen yang mengisi bidang layar. Maka, kata-kata di dalam bingkai atau layar gawai memiliki peluang untuk dapat dikonstruksi dalam suatu cara yang hampir sama, tapi perlu modifikasi, dengan bagaimana sebuah montase diterapkan sebagai gaya tutur berbahasa di dalam filem.
Ketika menerapkan “teori montase” untuk menganalisa diskursus teks pada media cetak (misalnya surat kabar), aspek ketubuhan menjadi soal yang umumnya tidak diperhitungkan. Karena, sederhananya, saat seseorang membaca, bagian yang aktif adalah hanya daya penglihatannya. Saat membalik halaman, daya penglihatan si pembaca akan berhenti sejenak (atau keluar/terputus sesaat dari “ruang cerap”). Mata dan tangan, masing-masing beroperasi secara terpisah. Dengan kata lain, tubuh si pembaca secara esensial pasif ketika proses pencerapan terjadi. Analisa mengenai hubungan aksi-reaksi antara objek dan subjek (surat kabar dan pembaca) menjadi tidak populer dalam konteks ini.
Sementara, pada gawai berlayar sentuh, walaupun para penganut paham distopia media menyebut tubuh-tubuh netizen menjadi tidak aktif karena gerak-gerik netizen mengerucut dan lebih berpusat pada gerak jari-jemari semata, daya penglihatan dan gerak tubuh justru terjadi secara bersamaan. Aksi menggeser beriringan dengan aksi melihat. Ketika menggeser image pada layar, perpindahan posisi antara elemen visual yang satu dengan yang lain demikian halus dan seakan-akan tidak disadari oleh user. Mekanisme ini sebagaimana halnya juga terjadi saat seseorang menonton gambar bergerak yang sesungguhnya adalah kumpulan dari gambar-gambar diam yang saling berganti posisi untuk tampil ke hadapan mata si penonton itu. Tapi, berbeda dengan menonton gambar begerak (video ataupun filem) di layar konvensional, pada kasus layar komputer atau gawai berlayar sentuh, tidak jarang sebuah gerakan (movement) dari image justru terjadi tatkala jari menyapu layar untuk menggeser posisi elemen-elemen visual, dan ketika jari melakukan “aksi menggerakkan” itu, daya penglihatan si user tidak terputus dari “ruang cerap”, terkadang malah terakumulasi pada kasus-kasus tertentu. Karenanya, wajar jika sering terjadi kejutan-kejutan, atau sering ditemukan peluang-peluang untuk membuat kejutan dengan memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada sifat interaktif dari teknologi komputer. Ketika konsepsi movement yang dibuahkan dari “aksi menggeser” ini dibingkai dan dipersoalkan, maka “struktur-non-sinkron” dapat dipahami sebagai hal yang bisa melahirkan spekulasi yang lebih imajinatif, baik dari sudut pandang komedi, atau upaya deformasi makna, atau spekulasi tentang ujaran-ujaran eksperimental. Yang jelas, itu semua tidak akan lepas dari konteks bagaimana si pengguna gawai yang tengah menyimak konten di dalam layarnya itu mencerap dan bereaksi.
Saya pikir, melalui Dispositif (atau mekanisme berpikir) seperti itulah, kemudian, puisi-puisi kontemporer @masdalu dan teks-teks pada kolom caption-nya bisa meraih penerjemahan yang signifikan dengan relevansi yang baru. Ia dapat menjadi suatu model bagi “sajak eksperimental” dalam budaya layar genggam kita hari ini. Kerangka berpikir dan interpretasi semacam ini pun, sebetulnya, dapat pula diterapkan pada konten-konten yang kita sebar atau kita konsumsi setiap menit di akun media sosial kita masing-masing, contohnya pada Instagram Stories. *
Catatan Kaki
(1) Jonas Mekas, “Filmmaker Jonas Mekas Skypes with Hans Ulrich Obrist about the rise of the .net generation”, wawancara oleh Hans Ulrich Obrist. Document Journal, 10 Juni 2015.
Esai ini adalah konstruksi baru dan pengayaan dari ujaran sepintas lalu di Instagram Stories @manshurzikri yang versi pra-revisinya sudah pernah di-share oleh penulis pada tanggal 22 April 2018.
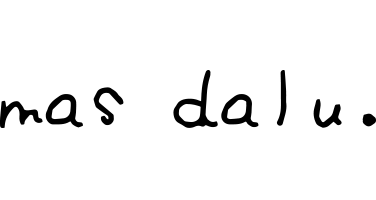
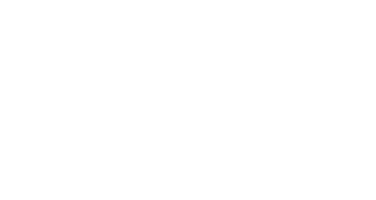
Sorry, the comment form is closed at this time.